Kalimat yang mewakili anganku, mengembara disetiap pelosok dunia.
Entah itu melalui berita-berita internasional di chanel-chanel televisi, radio atau ribuan kata di berita-berita koran.
Mesti begitu.
Mesti setiap aku akhiri setiap bacaan, tontonan atau pendengaran, selalu tak sanggup hentikan pengembaraan pikirku, pun tak selalu sanggup menuangkannya ditulisan sederhana, selain beberapa gelintir puisi dan kalimat-kalimat.
Begitu juga saat-saat ini.
Saat aku telah menjadi istri dari seorang Jawa, menjadi ibu dari seorang anak perempuan, serta bagian dari keluarga besar suamiku.
Maaf jika terkesan begitu sukuisme. Hanya ingin tegaskan maksud tulisanku kali ini.
Aku sendiri seorang Sasak tulen. Sampai pun tujuh lapis generasi ke-atas, tak ada darah suku lain dikeluargaku.
Dan saat mulai semakin mencintai kata-kata, menjelajahinya disetiap berita televisi, radio, tulisan-tulisan, aku sadar, sukuisme jauh lebih baik ditinggalkan sebagai teori dan pengetahuan. Dikehidupan nyata, perbedaan sudah begitu banyak. Terasa sangat tak layak mengedepankan Sasak-ku, dan melebihkannya dari yang lain. Untuk alasan yang sama pula, aku tidak bisa terima jika hanya karena aku orang Sasak, banyak nilai-nilai masyarakat, juga norma-norma, yag dianggap tak aku kuasai.
Semua suku, semua bangsa, memiliki nilai mereka masing-masing.
Diri kita pribadilah yang harus terus menempa diri, mengasah hati, untuk bisa menerima semua nilai tersebut, mengambil yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan pada akhirnya, berlomba melakukan kebaikan untuk meraih total kebaikan bersama.
Tentu belum hilang ingatan kita, hebohnya reaksi masyarakat atas Pengharaman Pluralisme Agama oleh MUI [link hanya salah satu judul berita dari banyak tema terkait]. Bahkan pun seorang Frans Magnis Suseno meng-amininya, walau tak lantas mengharamkannya.
Aku tidak ingin berpanjang kata untuk hal tersebut. Untuk diriku sendiri, memaknai pluralisme terasa cukup hanya dengan berusaha memahami, mengerti dan menyerap nilai-nilai terbaik yang ada dikeluarga besar suamiku.
Hampir tiga tahun sejak boyongan pertama dari Lombok, Juni 2004 lalu, jujur aku masih harus banyak belajar. Tak sedikit momen keterkejutan saat membaur diSemarang sini.
Contoh sederhana.
DiLombok sana, aku tumbuh dengan pengakuan kerendahan sebagai anak kepada orang tua disekitar, apalah lagi orang tua dirumah atau keluarga besar. Agak tabu untuk langsung membahasakan 'aku' dengan 'aku'. Kami di Sasak menggunakan 'tiang' sebagai 'aku' kepada yang lebih tua.
Jadi, saat diSemarang, aku cukup kaget mengetahui sebagian besar anak-anak membahasakan diri mereka sebagai 'aku' kepada siapapun.
Beberapa saat kemudian, dengan semakin membuka mata dan hati dengan banyak bacaan dan kenyataan, akhirnya aku sadar, bagaimanapun, aku tak bisa paksakan nilai yang aku yakini dikeberadaanku sekarang. Toh, diLombok pun, penggunaan 'tiang' untuk membahasakan 'aku' sudah semakin jarang. Dan penggunaan 'aku' semakin umum dan global.
Akan lebih kompleks saat tak sekali dua aku terpaksa menggunakan bahasa 'campur'. Terbesar tentunya komposisi Bahasa Indonesia. Pun tak sekali dua aku tak mampu pahami marah dan kecewa dari keluarga besar suamiku. Bukan apa-apa, kebiasaan tuturku belum mampu menyerap emosi dari bahasa-bahasa jawa tertentu yang baru aku kuasai. Tulus aku meminta maaf.



.jpg)



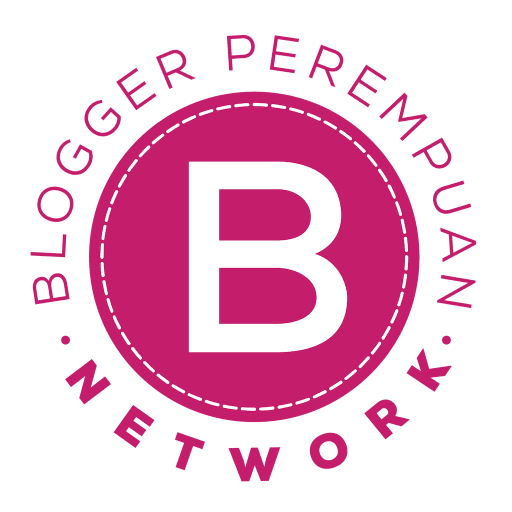
Post a Comment
Post a Comment